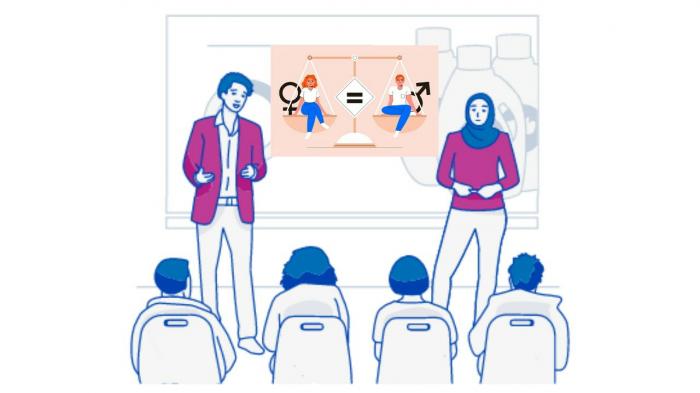
Pengantar gender lebih memudahkan mahasiswa agar menilai kualitas manusia bukan dari jenis kelamin, stereotipe yang dikhususkan pada gender tertentu, agar bisa saling menghormati sebagai sesama manusia, agar bisa saling membela dan melindungi ketika mendapat perlakuan yang seksis. Ah, atau sepertinya terlalu manja jika menunggu diwajibkannya pengantar gender untuk matkul maba. Wahai ormawa yang berburu kader di angkatan baru, ayolah adakan kajian gender yang mumpuni. Rutinkan, perluas perspektifnya, kalau bisa buatlah aksi turun ke jalan, ya aktualisasi diri juga ‘kan itu? Atau tak usahlah aksi-aksi kalau sekadar seremonial belaka. Lalu harus bagaimana?
retorika.id- Menjadi tua bisa diukur dengan berapa angkatan di bawah kalian. Sebagai mahasiswa tingkat (agak) akhir, sebaiknya perkara kemaslahatan angkatan baru mendapatkan perhatian kembali. Kalau bisa jangan lepas tangan mentang-mentang udah tuwir. Ya, tak terasa kampus kita tercinta menyambut mahasiswa baru (maba) lagi.
Sejak periode 2015, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) bagi maba di semua fakultas di Unair terdiri dari Agama I, Kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Agaknya kesemuanya merupakan materi yang mainstream karena telah kita dapatkan sejak SD hingga SMA. Lalu kenapa ketika status sudah naik menjadi sang “maha”, materi yang didapatkan masih sama saja dengan sang siswa?
Ah, lagaknya itu siasat mencegah radikalisme di lingkungan kampus.
Ah, rupanya agar kita tidak melupakan akar semangat nasionalisme.
Ah, sepertinya indoktrinasi negara harus terus diulang melalui berbagai lembaga.
Ya, mungkin bisa jadi seperti itu.
Entah, itu hanya asumsi liarku.
Eh, atau karena gelagat pemerintah mudah terbaca?
Mungkin begini perlunya kelima MKWU yang sudah ada ini.
Bahasa Indonesia berguna untuk berbagai keperluan, untuk keperluan menulis utamanya. Masa’ mahasiswa, dari SD sampai kuliah, menulis yang sesuai dengan kaidah saja tidak bisa. ‘Masalah penggunaan di- dipisah atau digabung saja tidak bisa. Huh. Dosen sekali pun luput. Membuat daftar pustaka saja tidak bisa. ‘Kan memalukan. Mungkin begitu.
Bahasa Inggris. Wah, karena globalisasi. Individu dituntut agar lebih kompetitif dengan mengutamakan calon pekerja yang lancar berbahasa Inggris, bahasa internasional. Bahasa Inggris membantu mahasiswa dalam keperluan tulisan akademiknya, tidak mudah terkena plagiasi, karena terbiasa menarasikan dari jurnal internasional.
Agama, katanya mengajarkan nilai-nilai moral. Tapi juga berarti menyeragamkan materi kuliahnya berdasarkan aliran yang dominan di Indonesia, menyimpangkan yang berbeda, bahwa hanya ada satu kebenaran.
Kewarganegaraan, melupakan perbedaan, menggaungkan kesatuan. Agaknya yang memicu penyortiran untuk keseragaman di masyarakat, melupakan keindahan toleransi dalam keberagamaan.
Pancasila, dasar negara, mewadahi berbagai kepentingan dominan saat itu, menebak-nebak isu urgent yang berlaku terus-menerus. Terlalu idealis sepertinya. Juga kalau dilihat-lihat kurang spesifik dalam mewadahi isu-isu sosial yang menjadi masalah di Indonesia. Tapi katanya lima sila itu membungkus semua persoalan? Ya katanya sih.
Lalu kenapa kelima mata kuliah itu diberikan lagi pada maba?
Mungkin yang jadi pembeda adalah materi yang konon lebih “berkualitas”, diajar oleh tenaga (buruh) pendidik yang lebih profesional, demi mencetak agent of change yang berguna bagi bangsa. Herannya, ada pendidik materi kewarganegaraan tapi berlatarbelakang saintek. Bukannya bermaksud merendahkan. Tapi bukannya untuk materi kuliah yang jelas-jelas membutuhkan pengetahuan soshum yang mendalam, bukankah lebih baik mengambil pengajar dari soshum juga?
Oh, iya. Aku lupa. Ilmu sosial ‘kan dianggap seremeh itu sehingga banyak “anak” IPA bisa merebut jatah “IPS”. Problem yang berlangsung dari SMA hingga jenjang kuliah. Seperti takdir ilmu sosial itu sengaja dipinggirkan. Seakan semuanya bebas berbicara tentang perkara sosial, walau itu bukan bidang spesialis yang digeluti. Oh, apa itu agenda terselubung agar pengetahuan mapan tentang ilmu sosial tidak dikuasai oleh masyarakat?
Ah, isu sosial. Sering dibicarakan tapi tidak diprioritaskan.
Kembali lagi dengan MKWU. Materi yang sama diulang-ulang. Membosankan. Sudah tertebak lah alur dongengnya seperti apa, kebenaran yang didiktekan seperti apa. Maba dianggap sebagai cangkir kosong yang dengan mudahnya bisa diisi pikirannya oleh benih-benih ciptaan kampus.
Hanya saja, MKWU tersebut apakah memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkaya perspektif mahasiswa untuk berpikir kritis? Jika kebenarannya bersifat mutlak, lantas untuk apa ada ruang-ruang diskusi?
Justru, menurut penulis, ada mata kuliah yang luput sebagai bahan pendidikan wajib bagi maba. Namanya Pengantar Gender. Bukan, tidak perlu yang terlalu teoretis sekali, mengingat tak semua jurusan “butuh” mendalami materi ini. Hanya saja, sebagai manusia yang berkesempatan mencicipi pendidikan tinggi, ini adalah sebuah keharusan untuk dipelajari. Sebab nilai mahasiswa juga ditentukan dari perubahan yang bisa ia buat melalui lingkup terkecilnya, dari
circle-nya, yang bisa berarti bagi significant other-nya, bisa melalui peer group, keluarga, lingkungan organisasi, tetangga (iya kalau bersosialisasi), dsb.
Kekesalan selama hidup sebagai mahasiswa mengantar penulis untuk mengajukan mata kuliah pengantar gender sebagai MKWU. Titik yang paling signifikan adalah ketika masa KKN. Saat itu penulis menghadapi kenyataan bahwa ujaran dan tindakan seksis adalah sebuah pewajaran, bukan hanya bagi masyarakat pedesaan, melainkan di lingkungan mahasiswa sekali pun, bahkan mahasiswa dari kampus oranye yang dielu-elukan sebagai pendobrak perubahan itu.
Ketika penulis mencoba memberi informasi tentang seksisme, patriarki, masyarakat yang misoginis, ada saja yang beranggapan bahwa penulis terlalu kiri, radikal, liberal, bahkan dianggap lupa dengan agama. Ya faktanya penulis memang mendapat mata kuliah gender dari seorang Guru Besar di bidang gender. Faktanya banyak praktik “keagamaan” itu hanya akal-akalan untuk melanggengkan patriarki. Oh maaf, bukan agama. Tapi budaya yang secara subtle dimasukkan ke dalam rongga-rongga ajaran agama di masyarakat Indonesia.
Selain dari pengalaman KKN, penulis juga merasakan keparahan dari tidak pekanya mahasiswa dengan isu gender, dalam pengalaman kepanitiaan. Ujaran seperti “yang laki saja yang jadi pemimpin”, kepasrahan mahasiswa perempuan, dan tidak terdorongnya untuk memperlakukan para mahasiswa secara setara tanpa diskriminasi gender, itu mengesalkan. Jika memang tidak ingin menjadi pemimpin, kenapa harus membawa dalih bahwa penghambat kepemimpinan itu berdasarkan gender?
Ada lagi pengalaman yang mengesalkan. Ketika diskusi antar ormawa di kampus, dengan presensi beberapa ormawa yang getol melakukan kajian literasi, yang membela hak-hak buruh, tapi secara sadar (atau ketidaksengajaan yang disengaja, atau membudaya) melanggengkan praktik-praktik yang misoginis. Verbal harrassement pada mahasiswa perempuan dibicarakan dalam forum, dengan nada guyon, dengan dalih agar suasana tidak terlalu kaku. Bukankah itu mengesalkan? Candaan seksis itu hinaan, itu pelecehan. Waktunya untuk menghentikan lingkaran setan itu. Membahagiakan banyak orang dengan mengorbankan beberapa orang itu bukan kebahagian yang utuh namanya.
Perjuangan tentang kelas bukan hanya tentang status ekonomi belaka, jangan lupa bahwa isu gender juga harus diperjuangkan karena secara jelas itu memproduksi “kelas” berdasarkan jenis kelamin. Akar dari diskiriminasi paling sederhana terlihat dari diskriminasi gender, karena itu hanya berdasarkan jenis kelamin loh. Penulis merasa itu basis paling sederhana dalam menyoal diskriminasi, dan itu malah diremehkan?
Jadi pengantar gender itu penting dipelajari. Mahasiswa harus berusaha menghapus kelas. Tak peduli seberapa apatis mereka, mereka harus, dituntut membawa perubahan.
Tapi belajar pengantar gender bukan berarti notok jedok belajar hanya dari perspektif perempuan. Ini juga sebenarnya PR untuk semua mata kuliah gender di berbagai jurusan, yang dominan dengan perspektif perempuan. Lama-lama bukan mata kuliah gender, tapi mata kuliah keperempuanan.
Iya tahu, perempuan adalah pihak yang paling disengsarakan dari patriarki. Namun bukankah laki-laki juga bisa menjadi korban dari patriarki? Walau dampaknya tidak seekstrim perempuan. Misalnya karena tuntutan menjadi pemimpin, akibatnya beberapa dari mahasiswa laki-laki merasa bertanggung jawab mengambil role tersebut, katanya naluriah, atau karena tidak percaya kepemimpinan perempuan? Tuntutan belum tentu membawa tanggung jawab, bisa jadi itu membebani. Akhirnya atas nama budaya, kepemimpinan diserahkan pada laki-laki, walau konsekuensinya leadership yang dilakukan asal-asalan, yang penting katanya mereka sudah berusaha.
Atau dalam kasus lain, kepanitiaan, dan KKN, seakan sudah seharusnya laki-laki bertugas menjadi tukang angkat barang, tukang servis, dan ojek. Bukankah semua orang sebenarnya bisa melakukannya? Ini sebenarnya juga masalah karena dalam beberapa masyarakat membiasakan nilai ini sejak kecil, terutama dari sosialisasi primer di keluarga. Jadi ketidakberdayaan perempuan juga bisa jadi karena bentukan nilai ini, diajari pasrah, diajari bergantung, diajari bahwa itu bukan wilayah mereka.
Namun mahasiswa juga sebaiknya berusaha memahami motif di balik tindakan, jangan terlalu cepat menggeneralisir. Terkadang memang individunya saja yang malas atau tidak mau melakukan sesuatu, tapi dinilai bahwa itu bawaan kodratinya karena gender. Huh. Menilai manusia jangan dari gendernya!
Alasan lain perlunya memasukkan perspektif laki-laki dalam mata kuliah pengantar gender ini adalah agar baik laki-laki dan perempuan bisa berjuang bersama demi mewujudkan kesetaraan gender. Sebab dalam beberapa hal, laki-laki diabaikan keterlibatannya dalam perjuangan kelas ini. Atau mereka terus disalahkan, tapi jarang dirangkul, jarang diajak berjuang bersama, seolah-olah masalah gender mutlak milik perempuan.
Ah, dan berbicara tentang laki-laki, sepertinya konsep toxic masculinity juga menjadi bagian penting agar mereka tak semakin arogan dan dengan lantangnya menghina berdasarkan indikator yang ... yah, tidak masuk akal (dalam beberapa hal). Misal, laki-laki dianggap kurang maskulin jika merawat diri, memakai skin care. Ehm, merawat diri bukan hanya masalah kecantikan, tapi juga merawat kesehatan, juga mempedulikan diri (self-care). Term kecantikan ini sendiri bermasalah karena sering diasosiasikan dengan perempuan. Padahal dunia kerja tak jarang menuntut penampilan yang menarik, tidak harus dengan visual lahiriah yang mumpuni, terlihat rapi atau menghargai penampilan diri itu dijadikan tolok ukur juga. Munafik jika para mahasiswa menolak eksistensi masa depan mahasiswa sebagai buruh korporat nantinya.
Jangan lupakan bahwa kasus revenge porn di kampus juga bisa jadi bagian dari toxic masculinity. Atas nama kegagahan, laki-laki diwajarkan menjadi pihak yang superior atas perempuan, menentukan harga perempuan, mendikte langkah perempuan. Kekerasan dianggap “baik” selama mendisiplinkan perempuan agar tidak “nakal”. Karena yang boleh nakal cuma laki-laki, realitasnya. Jangan lupa juga bahwa toxic relationship melanggengkan kekerasan atas nama membangun atau mempertahankan hubungan asmara.
Pengantar gender lebih memudahkan mahasiswa agar menilai kualitas manusia bukan dari jenis kelamin, stereotipe yang dikhususkan pada gender tertentu, agar bisa saling menghormati sebagai sesama manusia, agar bisa saling membela dan melindungi ketika mendapat perlakuan yang seksis. Misalnya, kenapa banyak pandangan miring terhadap mahasiswa perempuan yang merokok? Mahasiswa perempuan merokok dinilai menyimpang, tapi mahasiswa laki-laki yang melakukannya tidak dipermasalahkan. Masalah duduk dan cara makan juga dipermasalahkan. Tidak mencerminkan perempuan tulen katanya.
Pun juga pengantar gender mengantar mahasiswa agar tak menjadi hakim dari cara berpenampilan seseorang. Fashion bukan indikator gender. Mereka berpakaian untuk menunjukkan karakternya, bukan berarti untuk memuaskan mata orang (mahasiswa) lain. Pengantar gender juga bisa untuk mengantar mahasiswa agar tak menjadikan body shaming sebagai hobi. Menghujat berdasarkan cara atau gaya make up pula. Memang kenapa kalau dandanannya seperti itu? Toh materialnya juga tidak kalian sediakan. Memang kenapa kalau gayanya tidak cocok di mata kalian? Haknya dong, itu kebebasan berekspresi. Buat apa bergaya yang “cocok” tapi mengungkung nilai-nilai mereka? Boleh memberi masukan, tapi ujarkan secara personal, tidak dengan cara mempermalukan. Juga jangan menuntut! Kehidupannya adalah miliknya, bukan milik kamu, atau kalian.
Diharapkan pula bahwa tidak ada perundungan terhadap perempuan dari kain yang menyelimuti tubuhnya.
Berjilbab atau tidak, bukan kadar moralitas. Berjilbab panjang atau tidak, berjilbab dengan kain tebal atau tidak, bercadar, atau apa pun itu, bukan tolok ukur keimanan seseorang. Semua punya pilihan. Semua berhak dihargai atas pilihannya. Terlepas dari keyakinan terhadap kebenaran yang dianut.
Berpakaian gombrong, ketat, panjang, pendek, berkain tebal atau tipis, adalah kebebasan manusia dalam berekspresi. Perempuan dan laki-laki punya hak yang setara dalam menentukan pilihan berbusananya.
Pengantar gender juga sebenarnya berpotensi memperlambat pernikahan. Maksudnya karena tak sedikit dari mahasiswa menjadi budak irasionalitas bernama asmara, atau demi melegalkan seks, memutuskan untuk segera menikah. Atau mungkin tergoda menikah karena banyak teman sebaya yang menikah? Maksudnya, memperlambat usia pernikahan ini bisa jadi keuntungan untuk mencegah ledakan penduduk. Banyak penduduk, lapangan kerja sedikit, terus malah menyalahkan pemerintah karena banyak yang menganggur. Huh.
Juga agar memikirkan ulang bahwa hubungan asmara itu menjalin dua insan sebagai mitra, bukan atas dasar kepemilikan. Kalau mengakunya atas dasar “memiliki:, bukankah kepemilikan manusia atas manusia lain itu adalah bentuk eksploitasi? Eh. Menjadi mitra berarti berstatus setara.
Juga agar tidak memaksakan harus beranak dalam jumlah berapa, atau memaksakan harus punya anak laki-laki biar lebih afdol mewarisi trah keluarga. Juga agar masalah kontrasepsi tak hanya dibebankan pada perempuan. Masalah seks dalam hubungan juga harus melalui consent kedua pihak. Pun penekanan bahwa masalah finansial bukan sebagai kewajiban laki-laki. Perempuan berkarir perlu dihargai sebagai pemberi nafkah ekonomi keluarga, bukan sebagai penunjang nafkah kedua bagi keluarga. Sebab sering kali perempuan hanya dianggap “membantu” memberi nafkah. Padahal baik laki-laki dan perempuan berkontribusi sama dalam perekonomian keluarga.
Eh, juga agar bisa menghargai manusia tidak berdasarkan status romansanya. Mengata-ngatai jomblo, mengejek yang pacaran, merendahkan yang memutuskan tidak menikah, menuntut pasangan yang sudah menikah, dan seabrek ejekan lainnya.
Juga agar menghilangkan cara pandang yang menilai perempuan dari keperawananannya. Kenapa tidak pernah mempermasalahkan keperjakaan? Kenapa perempuan dinilai tidak utuh sebagai perempuan jika tidak perawan? Kenapa tidak bisa berlaku sebaliknya pada laki-laki? Kenapa pemuasan seksual tidak boleh dilakukan perempuan? Sedangkan laki-laki diperbolehkan melakukannya pada siapa atau apa saja. Juga agar konsep seksualitas dipahami sebagai hak setiap manusia, bukan hanya laki-laki yang diperbolehkan bebas mengekspresikannya. Perempuan harus dipahami sebagai subjek, bukan objek.
Mahasiswa juga harus sadar, bahwa yang salah adalah ketidakbecusan dalam mengontrol nafsu dan tanggung jawab yang dilempar-lempar, bukan karena kesalahan eksistensi perempuan. Bukan karena perempuan “mengundang”. Betapa norma sosial, bahkan regulasi mempersempit pemaknaan bahwa tubuh perempuan adalah “tubuh sosial”, di mana moralitas dilekatkan padanya. Tidak adil ketika laki-laki begitu dibebaskan dan dilazimkan atas berbagai hal, tapi tidak berlaku setimbang jika perempuan yang melakukan. Sudah banyak yang dirugikan akibat meluasnya victim blaming ini, aparatur negara juga tidak cukup menolong dengan menggunakan perspektif korban dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Ketidaktahuan tentang pemahaman gender ini membuat perjuangan dalam pengesahan RUU-PKS menjadi terhambat, karena masih dipahami banyak orang dengan kacamata yang salah. Akibatnya sulit mendapatkan payung hukum yang jelas untuk mengusut kasus kekerasan seksual.
Tarikan dari pengantar gender ini bisa juga bermanfaat agar kalian memperlakukan anggota keluarga kalian secara setara. Bahwa kedudukan ibu dan ayah adalah sama. Kalau bisa ya beri informasi secara halus agar mereka juga sadar gender. Atau jika kalian punya saudara, bisa ‘kan itu jadi topik obrolan, agar mereka menjadi manusia yang lebih berharga karena bisa menghargai orang lain. Bukan karena saudara laki-laki jadi harus menjaga saudara perempuan, tapi karena kalian adalah sesama manusia yang diikat oleh hubungan darah, maka kewajiban kalian adalah saling menjaga.
Memang tak semua mahasiswa berlaku dan berujar seksis, tidak semuanya seekstrim dari contoh-contoh yang dipaparkan oleh penulis. Tapi pasti ada ‘kan populasi yang sedemikian itu di kampus ini?
Lagi pula FISIP bukan garansi mahasiswanya tidak melakukan diskriminasi berbasis gender. Pun FISIP juga berarti satu-satunya fakultas yang dipasrahi untuk mendobrak sistem kelas ini. Kenapa tidak berjuang bersama?
Isu gender bukan isu sepele. Penulis tidak membenci laki-laki, yang harus dibenci dan dilawan adalah patriarki. Cara memulai perjuangan menuju kesetaraan gender bisa dilakukan melalui pendidikan. Ya universitas harusnya memberikan concern pada isu gender. Menuju World Class University harusnya peduli dengan isu-isu berkelas seperti ketidaksetaraan gender juga dong? Bukan hanya sekadar peduli, tapi turut andil dalam mengubah sistem yang busuk ini agar masyarakat bisa menjadi lebih beradab. Kampus bukan hanya pencetak tenaga kerja bukan?
Ini mungkin terdengar sebagai narasi yang naif nan membosankan. Tapi angkatan baru, dan angkatan-angkatan di bawahnya dalam beberapa tahun ke depan akan mengambil kendali dalam masyarakat. Jumlah mahasiswa angkatan baru ke bawahnya ini mungkin tak sebanding dengan populasi masyarakat Indonesia, namun dengan sedikit rasa optimis, ada kemungkinan bahwa ada beberapa individu yang mungkin akan menduduki posisi strategis nantinya, menguasai media, bekerja di parlemen, menjadi akademisi, atau pekerjaan lainnya, di mana isu gender bisa lebih digaungkan lagi agar benar-benar menjadi isu prioritas di skala nasional.
Ah, atau sepertinya terlalu manja jika menunggu diwajibkannya pengantar gender untuk matkul maba. Wahai ormawa yang berburu kader di angkatan baru, ayolah adakan kajian gender yang mumpuni. Rutinkan, perluas perspektifnya, kalau bisa buatlah aksi turun ke jalan, ya aktualisasi diri juga ‘kan itu? Atau tak usahlah aksi-aksi kalau sekadar seremonial belaka. Lalu harus bagaimana?
Penulis : Anita Fitriyani
TAG: #akademik #aspirasi #pendidikan #universitas-airlangga

 LPM Retorika FISIP Unair
LPM Retorika FISIP Unair
 @lpmretorikafisip
@lpmretorikafisip
 @ngs5967e
@ngs5967e
 @retorikafisipua
@retorikafisipua